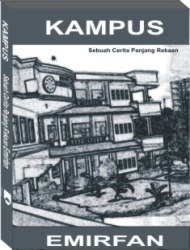Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa, dua bulan sesuai diwisuda, Danny mendapat kesempatan untuk bekerja di sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat. Maka, ia pun tidak pulang ke kota tempat ia lahir. Ia tetap berjuang di rantau.
Danny suka sekali pada job deskripsinya. Pekerjaannya sehari-hari adalah menerjemahkan teks bahasa Inggris menjadi teks bahasa Indonesia. Satu hal yang ia tidak suka adalah karena ia mendapat bayaran kecil dari lemabaga kecil tersebut. Selain itu, pembayarannya pun tidak terjadwal. Kadang tanggal tiga, bisa tanggal 15, ataupun akhir bulan. Juga bisa penuh, bisa setengah dari gaji, ataupun digenapkan saja menjadi berapa begitu. Karena memakluminya, Danny sanggup bekerja di sana sampai hampir satu tahun. Dan selama itu, ia belum bisa mengirimkan uang untuk keluarganya. Malah, ia masih meminta beberapa jumlah kiriman uang dari ibunya sekadar untuk membayar uang sewa kos dan makan di warung, tentunya tanpa sepengetahuan ayahnya. Untungnya Danny juga sering mendapat order terjemahan dari luar kantornya.
Di hari-hari terakhir bekerja di LSM tersebut, Danny benar-benar sudah tidak kerasan lagi bekerja di sana. Pasalnya, bayarannya semakin tidak jelas saja. Ditambah lagi karena beberapa hari sebelumnya, ia ditelepon perusahaan yang cukup besar. Perasaan malas itu semakin menjadi saat semakin dekat hari untuk psikotes dan wawancara di perusahaan tersebut. Sebenarnya, Danny adalah karyawan yang masih bertahan di sana. Sebelumnya ada lima orang yang bergiliran mengundurkan diri tiap bulannya.
Untuk hadir pada acara psikotes dan wawancara, Danny membolos di LSM itu. Ia sengaja tak memberi kabar karena dia yakin direktur LSM tersebut tak mencarinya. Rangkaian tes dan wawancara tersebut berlangsung selama tiga hari. Barulah hari keempat ia kembali masuk kantor bertemu dengan kejenuhan. Dua minggu kemudian, ia ditelepon kantor yang baru. Katanya ia diterima. Danny senang sekali dan langsung resign, mengundurkan diri dari LSM tersebut.
Semenjak bekerja di kantor yang lebih formal dan besar, Danny tak lagi meminta uang kiriman pada ibunya. Bahkan setelah setahun bekerja di sana, dia dapat mengirim uang untuk keluarga di kota kelahirannya.
Saat libur lebaran, Danny pulang ke rumah orang tuanya. Setelah selesai shalat ied, berkumpulan keluarga tersebut di ruang makan. Selain ayah dan ibunya, ada juga adik perempuan Danny yang masih kuliah.
“Dan, gimana kerja?” tanya ayahnya.
“Baik, Yah.”
“Ayah udah tua. Udah males nyari orderan. Udah males nyari duit, Dan.”
Semuanya masih menikmati makannnya sambil menunduk. Mereka agaknya sudah bosan mendengar ocehan orang tua itu.
“Ayah iri sama orang tua lain. Itu lho, bapaknya Hendra, temen SMA kamu, katanya tiap bulan dapet kiriman dari Hendra.”
Danny kaget. Ia merasa sudah mengirimkan uang yang lumayan untuk ayah, ibu, dan adiknya. Belum sempat ingin membantah, ibunya langsung memberi isyarat agar Danny diam.
Setelah makan selesai, ayahnya menuju ruang tamu. Ibunya menarik tangan Danny kemudian membawanya menuju ke dapur.
“Uang yang kamu kirimkan, ibu pakai untuk biaya kuliah Dini. Sisanya ibu tabung. Habisnya kalau ayah tahu ibu punya duit banyak, maunya belanja barang dagangan terus. Nimbun minyak tanah, beras, atau beli barang belanjaan sampai banyak sekali,” kata ibunya menjelaskan.
“O, gitu, Bu.”
“Iya. Jadi tolong kalau ayah bilang begitu, biarin aja ya, Nak.”
Danny bingung tapi mengangguk. Kemudian malam harinya, seusai sholat Maghrib, Danny menghampiri ayahnya yang sedang duduk di teras membaca koran. Suara takbir masih mengalun dari mushola yang tak jauh dari rumahnya. Ibunya dan Dini sedang mempersiapkan ketupat sayur untuk makan malam.
Danny menggenggam sejumlah uang kertas, lalu duduk di samping ayahnya. Danny memberikan uang itu. Ayahnya lalu tersenyum, “Simpan saja. Untuk bantu biaya kuliah Dini, atau tabung seperti ibumu.”
Danny semakin bingung, lalu ayahnya sedikit menjelaskan, “Sebenarnya ayah tahu kalau kamu kirim uang buat ayah walaupun uang itu nggak pernah sampai ke tangan ayah. Walaupun ibu nggak pernah bilang kalau dia menyimpan uang itu, ayah tahu. Mana bisa Dinny kuliah di luar kota hanya dengan hasil dari warung kecil kita.
“Jadi ayah pura-pura nggak tahu?”
Ayahnya tersenyum, “Yang paling mengerti ibumu ‘kan ayahmu”, beliau lalu berdiri mengajak Danny makan ketupat.
Yogyakarta, 11 Agustus 2008
Kamis, 12 Maret 2009
Langganan:
Komentar (Atom)